Jurnal Awal dari Serambi Madinah
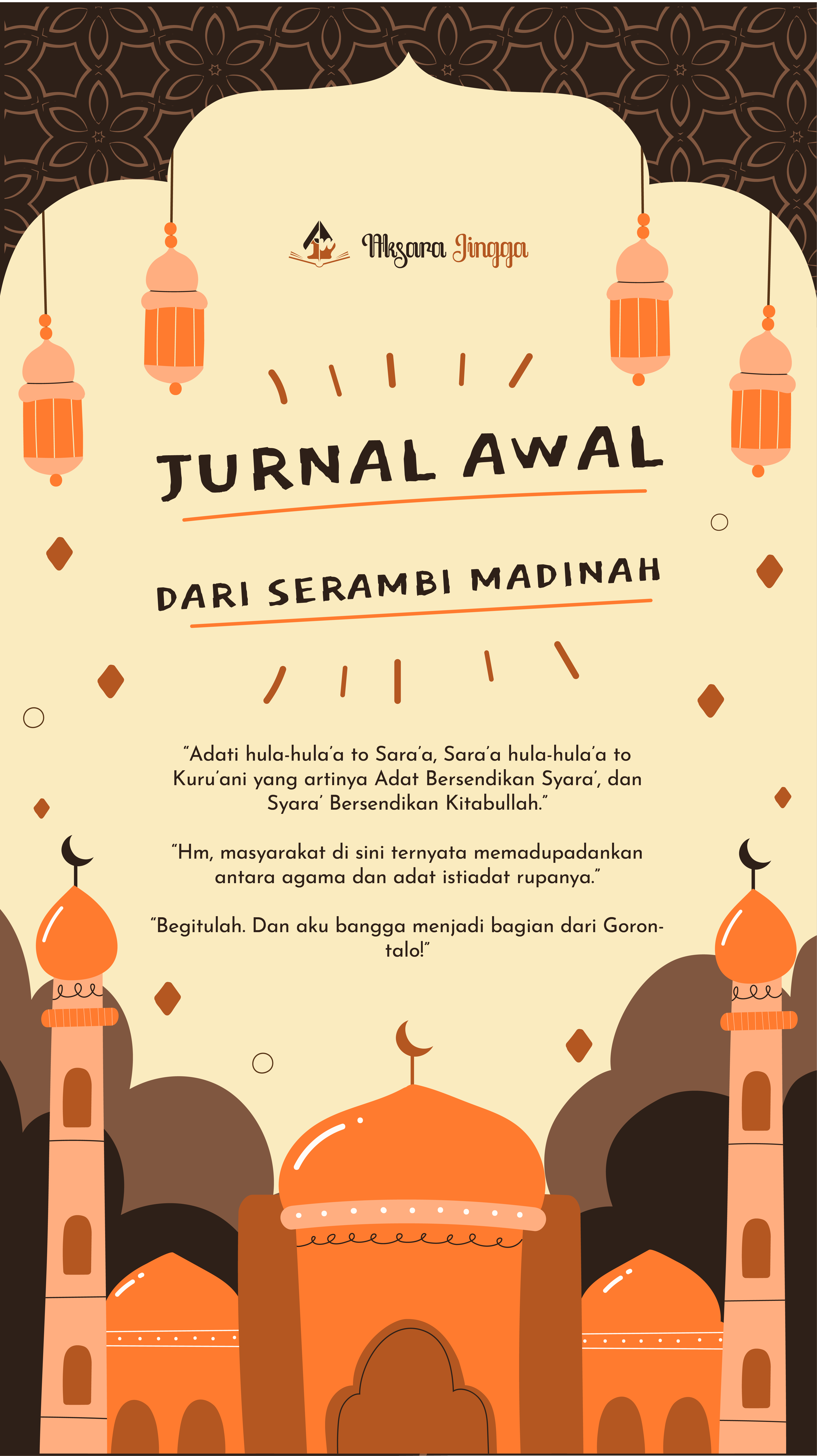 |
| Jurnal Awal dari Serambi Madinah - AksaraJingga.Com |
Karya oleh Ri Khairya
Awan putih terhampar bak kapas mengambang di langit. Di bawah sana terlihat rumah-rumah penduduk yang terlihat padat. Aku memperbaiki dudukku, mencari titik nyaman. Saat ini aku tengah berada di pesawat tujuan Gorontalo. Sebuah kota dengan sebutan Serambi Madinah, julukan yang muncul karena manifestasi nilai adat, nilai kesopanan dan nilai norma agama yang dijunjung tinggi oleh warga setempat.
Bukan keputusan mudah bagiku untuk bepergian sendiri. Apalagi aku adalah tipe orang yang tak bisa jauh dengan orang tua. Akan tetapi, aku harus berangkat. Di sana ada rumah Bude Wulan, tempatku tinggal nanti. Ah, aku jadi kangen dengan suasana di rumah Bude Wulan. Bisa kubayangkan Ranti mengoceh sepanjang hari, sepupuku yang satu itu memang cerewet tapi aku menyukainya. Tak sabar rasanya segera mendarat di sana. Benakku diam-diam menebak, siapa yang akan menjemputku kali ini? Semoga saja Ranti, ada banyak hal yang ingin aku ceritakan padanya.
Benarlah. Ranti melambai dengan riangnya ke arahku. Ia ditemani Pakde Agung.
“Icha,” panggil Ranti. Suaranya yang keras sontak membuat beberapa orang menoleh, terkaget mendengarnya.
Aku terkekeh sambil membalas lambaian tangannya. Menyapa Ranti dan Pakde Agung. Berbasa-basi sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Bude Wulan. Sepanjang jalan bisa kudengar celoteh Ranti, dia memang pada dasarnya cerewet. Ah, menurut salah satu kepercayaan apabila seseorang memiliki tahi lalat di dekat bibir maka ia akan cerewet, bukankah begitu? Aku sih percaya karena nyatanya Ranti memiliki tahi lalat di bawah bibirnya. Ya, meski aku tidak tahu keakuratan dari kepercayaan itu.
“Kau tahu semboyan kami?” tanya Ranti. Membuyarkan lamunanku barusan, membuatku sempat terkesiap sejenak. Aku menggeleng. Aku bukan penduduk setempat, lagi pula penduduk setempat terkadang tidak mengetahui secara jelas mengenai kampung halamannya sendiri. Benar toh?
“Adati hula-hula’a to Sara’a, Sara’a hula-hula’a to Kuru’ani yang artinya Adat Bersendikan Syara’, dan Syara’ Bersendikan Kitabullah.”
“Hm, masyarakat di sini ternyata memadupadankan antara agama dan adat istiadat rupanya.”
“Begitulah. Dan aku bangga menjadi bagian dari Gorontalo!” unjuk Ranti.
Aku tersenyum kecil melihatnya. “Kalau begitu, aku bangga menjadi bagian dari Bogor!”
“Yang paling penting, kalian bangga ada di Indonesia!” kata Pakde Agung. Kami berdua hanya mengangguk menanggapi pernyataan itu.
“Sebentar lagi bulan puasa, ya?” tanya Ranti.
“Ya, besok kan?”
“Biasanya di Bogor ngapain?”
“Di sana ada yang namanya munggah, sebuah tradisi di mana biasanya keluarga berkumpul atau apa pun itu. Biasanya aku sama teman-teman ngadain cucurak.”
“Cucurak?”
“Kayak tradisi di mana kita kumpul-kumpul sebelum Ramadhan, biasanya buat mempererat tali silaturahmi.”
“Begitu. Tau enggak kalau di Gorontalo ada yang namanya upacara Tonggeyamo?”
Aku kembali menggelengkan kepala. Sepertinya aku harus menegaskan pada Ranti kalau aku bukan penduduk setempat dan jelas tak tahu menahu mengenai adat asli Gorontalo. Lagi pula aku bukan tipe manusia yang menyukai sejarah hingga tahu seluk beluk adat di seluruh Indonesia.
“Upacara Tonggeyamo, semacam rukyat bulan muda atau hilal. Biasanya dilaksanakan 3 hari sebelum Ramadhan oleh dua orang udulaa atau kepala kampung. Habis itu dilaporkan hasilnya ke camat. Nah, camat biasanya didampingi pegawai sara’ atau urusan agama dan mayuru da’a atau kepala keamanan. Mereka itu disebut buwatulo towulongo.”
“Habis dilaporkan terus gimana?”
“Setelah itu esoknya, biasanya habis magrib sih, buwatulo towulongo bersama wali-wali dan petugas hantolo—“
“Petugas apa tadi? Hantaran?”
“Petugas hantolo, Icha. Penabuh genderang.”
“Sepertinya Icha sudah siap menikah sampai menyebut hantaran segala,” guyon Pakde Agung. Hal itu ditimpali oleh tawa Ranti, membuatku sedikit malu meski menyangkal. Umurku masih muda, belum siap untuk dikatakan siap menikah.
“Lanjutkan penjelasannya, Ran.”
“Ya habis itu mereka menghadap Bupati atau Walikota buat melaporkan hasil Tonggeyamo. Biasanya sih dilaporin di yiladia atau sebut saja rumah dinas.”
“Tiap-tiap daerah memiliki adat tersendiri rupanya,” kataku pelan.
“Itulah indahnya Indonesia, Icha.” Pakde Agung menimpali percakapan kami. Dari tadi ia memang menyimak, sesekali mengangguk menanggapi kami.
Tak banyak perbincangan setelah ini. Lagi pula aku kelewat lelah setelah perjalanan panjang. Mataku saja sudah berdemo karena mengantuk. Suara Ranti mulai terdengar samar hingga akhirnya aku bergelut dengan mimpi. Badanku memang sudah mengirimkan signal kelelahan setelah keluar dari Bandara. Aku cukup lemah untuk bepergian dengan jarak jauh. Apalagi kalau naik mobil, pusingnya membuatku ingin muntah seketika. Serasa berada di wahana komidi putar, membuat kepala pening. Memang yang terbaik ialah tidur.
Tadi sekitar jam 2 siang kami sampai di rumah Bude Wulan, sampai-sampai aku langsung tidur karena lelah yang mendera. Dasar aku! Bahkan, koperku saja masih belum dibuka dari tadi. Saat ini kami baru pulang dari masjid, sehabis terawih malam pertama. Ya, besok adalah Ramadhan. Hari pertama puasa di kampung orang memang berbeda ya sensasinya.
Baru selesai meletakkan mukena di meja, Ranti sudah menarikku, meletakkan sebuah wadah di tanganku.
“Pakai ini kalau mau keramas ya. Kulit kepalamu pasti gatal setelah perjalanan jauh.” Wadah yang Ranti sodorkan tercium begitu semerbak. Penasaran, aku mengintip isinya.
“Apa ini? Shampo keluaran terbaru?” tanyaku tak mengerti.
“Bukan, itu namanya bungo musa.”
“Bungo musa?”
“Iya, dibuat dari kelapa tua terus diparut. Setelah itu dicampur dengan daun pandan dan serai yang sudah diiris tipis-tipis. Habis itu disangrai deh. Selesai,” jelas Ranti. “Kau tahu? Bungo musa ini hanya ada di bulan Ramadhan. Nah, berhubung kau kemari pas mau bulan Ramadhan, Ranti hadiahkan itu untukmu.”
“Ah, terima kasih.”
“Sekarang mending bantu Ibu di dapur, yuk.”
Aku mengangguk pelan. Bude Wulan tengah memasak daging ayam, katanya untuk sahur nanti. Tinggal dipanaskan saat waktunya tiba.
“Bude masak apa?” tanyaku. Makanan yang tengah Bude siapkan terlihat aneh di mataku yang terbiasa melihat makanan khas Bogor.
“Ini namanya pilitode lo maluo, semacam kari ayam, makanan khas kami,” jawab Bude Wulan.
“Kau tahu, aku lebih suka makan tiliaya,” tukas Ranti.
Aku menoleh tidak mengerti. Nama-nama makanan itu terlalu rumit di lidah Sundaku.
“Tiliaya itu adonan santan dan telur yang dicampur dengan gula jawa, kemudian dikukus. Biasanya disajikan di sahur pertama. Konon katanya dapat memberikan kekuatan dan daya tahan tubuh ketika berpuasa,” jelas Bude Wulan.
Aku manggut-manggut mendengarnya. Belum sehari aku disini, aku sudah terpana akan adat budaya dari Gorontalo ketika Ramadhan. Sebuah kekayaan Nusantara yang patut dilestarikan.
“Mau tahu yang lebih meriah?” Ranti menaikturunkan alisnya, membuat rasa penasaranku muncul.
“Apa?”
“Tradisi tombilotohe. Disini biasanya memasang dan menata lampu tradisional di halaman maupun tepi jalan. Biasanya diadakan selama tiga malam berturut-turut dimulai malam tanggal 27 Ramadhan.”
“Oke, cukup membuatku penasaran, Ranti. Kau tahu aku akan menghabiskan sebulan penuh di sini. Jadi, jangan terus-terusan membicarakan hal yang membuatku tak sabar untuk segera melihatnya.”
Ranti dan Bude Wulan tertawa mendengar pernyataanku. Baik, mereka cukup menyebalkan. Aku rasa kedepannya akan ada banyak hal baru yang aku temui. Belum 24 jam saja mataku sudah menemukan fakta unik dari Gorontalo.
Serambi Madinah, tunggu aku mengeksplor budayamu!

